Tanggung Jawab Sosial Psikiater (Sekelumit Pemikiran Awal)
Pernah terlintas dalam khazanah mental, ihwal “tanggung jawab sosial psikiater”, _psychiatrist’s social responsibility_. Hal ini menggugat kemapanan di dalam klinik dan di dalam laboratorium. Psikiater ikut memikirkan masalah-masalah sosial-kultural, bahkan politis, di luar tembok-tembok klinik dan rumah sakit, berkarya di dalamnya, tetap sebagai _mental health helper_ yang bukan politisi. Misalnya, hasil studi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 15 Juli 2024 (_vide_ Koran Tempo, 18 Juli 2024), menegaskan bahwa indeks perilaku antikorupsi (IPAK) di Indonesia menurun. Pada rentangan antara nol (yang menggambarkan perilaku anti terhadap korupsi yang terendah) hingga 5 (yang mewakili tingkat tertinggi perilaku anti terhadap rasuah), skor tahun lalu adalah 3,92; tetapi tahun ini menurun, menjadi 3,85. Penurunan indeks ini bermaknakan sikap masyarakat yang kian “mengiyakan” korupsi, permisif terhadap rasuah. Sepeduli apakah psikiater dan organisasi psikiater terhadap masalah demikian?
Sharma, _et al._ (2021) menemukan bukti kuat dan konsisten di tengah masyarakat Vietnam, bahwa _petty corruption_ (korupsi kecil-kecilan di tengah kehidupan sehari-hari) berasosiasi sejalan dengan tingkat _psychological distress_; terdapat bukti yang cukup _(suggestive)_ bahwa kampanye antikorupsi berefek positif terhadap tingkat kesehatan mental; dan terdapat manfaat yang substansial upaya mengurangi korupsi dan peningkatan kepemimpinan yang baik untuk kesehatan mental. Sedangkan Zhang (2022) di China menemukan bahwa persepsi korupsi (pengalaman menyaksikan terjadinya korupsi di tengah kehidupan) merupakan faktor risiko yang penting untuk terjadinya depresi. Sementara Adjei, _et al._ (2024) menemukan di Ghana bahwa pengalaman para partisipan penelitian menyaksikan peristiwa korupsi di lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, serta persepsi bahwa kaum kaya dapat memengaruhi para pejabat untuk meraih keuntungan pribadi, berasosiasi kuat dengan depresi dan simtom-simtom ansietas pada partisipan-partisipan itu.
Di samping asli memiliki “motif menguasai”, otak-psike-pribadi senantiasa mengandung “motif berbagi”. Yang terakhir ini dapat secara deskriptif dinamakan “motif afiliatif altruistik”. Keberadaan kedua hemisferium yang tepat berdampingan dan terhubung satu sama lain, secara simbolis dan realistis menyatakan simultanitas _(simultaneity)_ kedua motif.
Motif menguasai bersumber pada struktur dan fungsi luhur hemisferium kiri. Sedangkan motif afiliatif altruistik berasal dari hemisferium kanan. Keberasalan itu tidak semata-mata biologis, tetapi juga relasional, eksperiensial, kultural, sosial, spiritual; karena kedua hemisferium mengandung kapasitas neuroplastis yang secara hakiki bermakna kemampuan untuk belajar dan mentransformasi diri dalam dan dari setiap pengalaman meneruskan kehidupan. Belajar dan transformasi berlangsung _from the cradle to the grave_, sepanjang hidup.
Namun dalam kenyataan, kehidupan sedemikian “dominan hemisferium kiri” dan “kurang bertitik berat hemisferium kanan”. Motif menguasai memang asli untuk diri, buat semata-mata diri sendiri. Alternatifnya adalah motif afiliatif altruistik, yang jelas untuk “diri-dan-liyan-dan-masyarakat-dan-lingkungan-dan-dunia”. Korupsi melaju lancar sekali dalam koridor “kehidupan untuk diri”. Seandainya bisa motif afiliatif altruistik dikuatkan dan dibesarkan kiprahnya, dan _Homo sapiens_ adalah insan pintar tak terutama buat diri tetapi untuk diri-dan-liyan-dan-masyarakat-dan-lingkungan-dan-dunia, kelajuan korupsi akan dapat dihambat. Menguatkan dan membesarkan kiprah hemisferium kanan ini merupakan pekerjaan rumah psikiater yang mencoba menunaikan tanggung jawab sosialnya.
(Limas Sutanto)
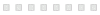
 FIRST ANNOUNCEMENT 3rd UCAPS 2025
FIRST ANNOUNCEMENT 3rd UCAPS 2025
 The 10th World Congress Asian Psychiatry (WCAP) 2024
The 10th World Congress Asian Psychiatry (WCAP) 2024





