Sombong, Bebal
Martin Jacques, seorang jurnalis, editor, dan akademisi dari Inggris, pandangannya luas, karena tatkala berupaya memahami suatu fenomena sosial ia senantiasa memerhatikan sejarah dan budaya. Seperti serupa dengan dokter yang berusaha mengerti simtom pada pasien dengan selalu memperhitungkan data dari anamnesis, serta dari kebiasaan dan kultur dalam kehidupan pasien.
Intelektual Inggris itu mengujarkan betapa dua keadaan ini, arrogance dan ignorance, sungguh menghambat pemahaman yang cukup baik. Kesombongan dan kebebalan bagaikan dua sisi dari sebuah koin. Kesombongan atau arogansi membendung arus masuk pengetahuan dan pengertian. Sedangkan kebebalan atau ignorance adalah miskinnya pengetahuan dan pengertian sebagai akibat dari keengganan untuk membuka diri agar dapat menerima mereka. Agaknya keangkuhan dan kebebalan kedua-duanya hampir serupa. Antitesis bagi mereka sekaligus, adalah kerendahhatian.
Seorang pasien yang mungkin disebut “menderita distimia” membikin terapisnya diam-diam jengkel, karena dalam hampir setiap sesi bercerita tentang pengalaman-pengalaman derita yang pernah terjadi dulu. Sembari bertutur demikian, pasien menghayati kesedihan yang kental, kadang disertai marah terhadap keadaan atau orang yang terkait dengan keterjadian penderitaannya. Terapis, kendati dibelit jengkel yang nirsadar, ingin menolong. Ujar dia, “Dirimu seperti terjebak dalam masa lampau, bahkan yang penuh derita. Engkau tidak menceritakan pengalaman masa lalu yang menyenangkan”. Sebuah interpretasi yang secara intelektual tidak keliru. Namun mungkin ia lahir dari arrogance dan ignorance sang terapis yang tak sudi menjadi rentan sewaktu perlu mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui.
Ketika waktu seperti bergulir perlahan sembari memberikan kesempatan bagi pasien ini untuk mengalami keadaan-keadaan baru yang bagus, kebiasaan terpaku pada masa lampau yang kaya derita, yang melelahkan, itu berkurang. Terutama perjumpaannya dengan seorang teman yang mau mendengarkannya dan berupaya dengan rendah hati memahaminya—di waktu kemudian teman ini menjadi calon pasangan hidupnya—memungkinkan ia makin sedikit bercerita tentang menderita di masa lalu. Kesedihan dan kemarahannya pun menyusut. Pasien mengatakan bahwa kadang ingatan tentang tempo dulu yang menyakitkan terlintas begitu saja, dan perasaan marah dan sedih tidak terhindar. Namun, kata dia, lintasan memori itu, dan emosi derita yang menyertainya, kini hanya berlangsung singkat saja.
Terapis bertanya, “Keadaanmu kini lebih baik, meskipun belum seluruhnya. Menurutmu, bagaimana perbaikan ini dapat terjadi?” Pasien tak langsung menjawab pertanyaan yang sukar ini. Ia terdiam beberapa saat sebelum mengatakan, bahwa perbaikan terjadi seiring dengan makin banyaknya pengalaman lain, yang baru, yang bagus, yang seperti mengubah pengalaman-pengalaman derita yang lama.
Saat itu terapis ingat bahwa dua tahun yang lalu ia pernah menghakimi pasien dengan mengatakan bahwa dirinya terjebak dalam masa lampau penuh derita dan tak hendak mengingat pengalaman yang bagus. Ia pun mengingat betapa waktu itu lontaran interpretasinya menghantam pasien, membuatnya sedih lebih mendalam, sampai hampir menjadikan hubungan terapi berakhir. “Ucapan itu tidak membantu saya”, tutur pasien waktu itu. Terapis dihadapkan pada kesadaran bahwa dirinya sombong dan bebal. Banyak tidak tahu tentang pasien, tetapi merasa tahu dan sesungguhnya menolak untuk tahu. Ke depan dia memiliki rancangan mengolah kedua kecondongan itu untuk dirinya yang, seperti dikatakan oleh Bion, seyogianya menjadi sebuah container.
Fenomena “pasien hampir dalam setiap sesi menceritakan pengalaman lampau yang mengandung derita, sembari merasakan afek atau emosi yang menjadi unsur-unsur pengalaman itu”, membeberkan sebuah peristiwa psikis yang oleh Freud disebut Nachträglichkeit. Oleh Lacan dinamai aprés-coup. Di sini kiranya boleh disebut “ketertundaan”. Sekadar melihat ke tempat lain, Nachträglichkeit berpadan kata dengan afterwardsness, atau retroaction, dan deferred action.
Semula pelopor primer psikoanalisis itu menyaksikan betapa suatu pengalaman traumatis acap kali tidak berefek derita di seputar saat terjadinya. Pengalaman tersebut cenderung direpresi sehingga tidak disadari, tak terasa, kendatipun tetap menjadi bagian dari dunia hidup insan yang mengalaminya. Di suatu saat, jauh ke depan, sesudah menjalani ketertundaan yang cukup lama, ada saja peluang yang kondusif buat terejawantahkannya pengalaman derita yang tertunda. Tidak jarang peluang tersebut terdapat dalam relasi terapeutik antara insan dan terapisnya. Atau dalam kesempatan-kesempatan lain pula.
Derita sedih dan marah mendalam di suatu saat dalam kehidupan, sesudah terepresi lama, mungkin kini mendapatkan tempat untuk terealisasi. Pasien lantas terlihat sering sedih mendalam dan marah keras. Perlukah ini semua dibendung, atau bahkan ditiadakan, dengan cepat, dengan aneka cara yang bahkan disebut “ilmiah” sekalipun?
Tidak jarang dalam sesi psikoterapi, terapis menyadari Nachträglichkeit. Ia mengalami sedih dan marah pula, tetapi ia dapat meregulasi kedua-duanya. Dalam pendidikan dan pelatihan terdahulu, dia mengalami upaya mengolah afek yang keras, bahkan membanjir. Pengalaman itu kini diejawantahkan dalam regulasi afek yang efektif dan bagus. Percayakah, tatkala pasien beriwayat trauma itu berelasi terapeutik dengan terapis ini, ia pun belajar mengolah afek marah yang keras dan sedih yang mendalam? Semua ini ikut menjadi pengalaman-pengalaman baru, yang bagus, dalam khazanah kehidupan afektif pasien, yang dapat terakumulasi memadai buat mengubah pribadinya yang selama ini dinamai “distimik”.
Kadang ada kesan psikiater itu, bagaimana pun, adalah “ahli pengobatan”. Mereka memiliki privilese buat meresepkan obat, sekaligus terkesan seperti tidak lancar melaksanakan pembantuan psikologis selain mengobati. Urusan psikoterapi dianggap sebagai tugas psikolog. Namun rasa-rasanya di samping psikolog, psikiater pun bisa, patut, dan seyogianya membantu secara psikoterapeutik. Kalangan luas “ilmu-ilmu psikologi”—di dalamnya terdapat antara lain psikologi dan psikiatri—memerlukan mengatasi dan menjauh dari arogansi dan ignorance yang menghambat.
Link Partner
Peranan Psikiater Dalam Kasus Hukum
Psikiater memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sebuah kasus hukum, baik untuk membuat visum et repertum maupun sebagai saksi ahli. Psikiater yang mengkhususkan diri pada hal tersebut, disebut psikiater forensik atau konsultan forensik. #psikiater #forensik #pdskji #pdskjiindonesia #dokter #kasushukum #kesehatan #kesehatanmental #pengadilan #dokterspesialis
https://www.instagram.com/reel/Cqt5XUiO4Ug/?igshid=MDJmNzVkMjY=Skizofrenia dapat disembuhkan, apakah benar?
Paradigma pengobatan skizofrenia saat ini telah bergeser, termasuk pemilihan terapi antipsikotik injeksi atau disebut atypical antipsychotic long-acting injectable (aLAI). Yuk, ikuti e-Course CEGAH KAMBUH SKIZOFRENIA terbaru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan orang dengan skizofrenia! GRATIS! Dapatkan 6 SKP IDI serta Sertifikat PDSKJI Tanpa biaya! e-Course ini dipersembahkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) bekerja sama dengan Alomedika serta didukung sepenuhnya oleh Johnson & Johnson.
KLIK link ini! https://alomedika.onelink.me/qZen/92164225Cari Dokter
Login Member
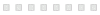
Event Yang Akan Datang
-
 FIRST ANNOUNCEMENT 3rd UCAPS 2025
FIRST ANNOUNCEMENT 3rd UCAPS 2025
06 Februari 2025 - Mari siapkan diri untuk agenda ilmiah Psikiatri Anak & Remaja paling dinanti! Departe...Readmore »
-
 The 10th World Congress Asian Psychiatry (WCAP) 2024
The 10th World Congress Asian Psychiatry (WCAP) 2024
05 Desember 2024 - the 10th World Congress Asian Psychiatry (WCAP) 2024 Presents International Symposium &am...Readmore »
Video Terbaru
Copyright © 2014 - PDSKJI - All rights reserved. Powered By Permata Technology





